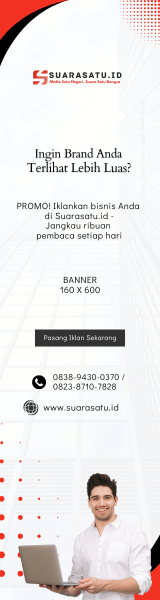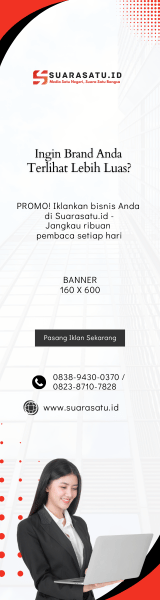Penulis: Adnan R. Abas
SUARASATU.ID – Tanggal 30 Juli 2025, sebuah pemberitahuan dari BMKG mengguncang ruang digital dan psikis masyarakat Gorontalo. Tsunami dinyatakan berpotensi menghantam pesisir utara, sebuah kemungkinan yang menyalakan trauma kolektif. Dalam hitungan menit, jagat maya dibanjiri unggahan, pemberitahuan, dan pemberitaan: sebagian edukatif, sebagian sensasional, sebagian lainnya kehilangan arah. Juga, tak luput dari beberapa kalangan turut meresponnya dengan lelucon—sebagai upaya untuk meredam kepanikan.
Tsunami, sebelumnya memang pernah terjadi di Indonesia, dekatnya di Aceh pada tahun 2004, dan di Palu 2018. Hal ini tentu membuat efek “traumatik” kepada korban, keluarga, dan seluruh penduduk di Indonesia. Tak terkecuali masyarakat Gorontalo itu sendiri.
Sejak pemberitahuan oleh BMKG itu diedarkan, masyarakat Gorontalo—contoh dekatnya masyarakat pesisir Pantai Biluhu dan Batudaa Pantai, bergegas untuk mengungsi ke dataran tinggi: Gunung.
Di sana, mereka mendirikan tenda pengungsian; ruang untuk bercakap atas apa yang akan terjadi ini (Tsunami). Lanskap ini, jika ditonton lebih dalam, akan mengundang airmata. Di suasana itu, terselip rasa haru mendalam—tentang rasa berharap akan tetap hidup: orangtua menenteng anaknya; bapak-bapak yang menyiapkan peralatan posko; dan beberapa remaja yang bercakap atas “apakah ini akan benar-benar terjadi?”
Namun di tengah kepanikan dan banjirnya informasi tsunami ini—ada yang perlu untum kita bedah bersama: bahwa tsunami, adalah “Berita” yang lebih ditakuti sekarang tinimbang “Derita” yang tak kasat mata.
Berita tsunami kali ini, saya pribadi memaknainya bukan sebagai peringatan geologis, tetapi juga sebagai metafora. Ia adalah pantulan dan analogi dari sistem kita: bahwa negara terlalu banyak menginstrusikan tanpa mendengar harusnya apa yang dibutuhkan oleh mereka.
Pemerintah lebih banyak membunyikan sirene-nya (himbauan dan edaran), tetapi sering alpa pada suara-suara rakyat yang terpinggirkan: suara orang miskin, anak-anak putus sekolah, dan para pemuda yang kehilangan arah atas kurangnya lapangan pekerjaan.
PENDIDIKAN DI GORONTALO YANG TIMPANG: SUARA INI TERPINGGIRKAN
Pendidikan seharusnya menjadi jalan pembebasan dan pemberdayaan, tetapi di Provinsi Gorontalo, realitas menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak daerah yang tertinggal di belakang.
Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 mencatat bahwa, presentase “tertinggi” penduduk yang mengenyam pendidikan, berada pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), yakni sebesar 32,75 persen.
Sekilas angka ini tampak menggembirakan, namun jika ditelisik lebih dalam, data ini justru menunjukkan adanya jurang ketimpangan: mayoritas warga Gorontalo tidak mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan sebagian besar lainnya bahkan berhenti sebelum sampai ke jenjang itu.
Lebih dari itu, data juga menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak mendominasi akses pendidikan sebesar (74,84 persen) tinimbang presentase laki-laki yang ada di Provinsi Gorontalo.
Dominasi ini lebih merepresentasikan fenomena pergeseran sosial ketimbang keberhasilan kebijakan pendidikan.
Perempuan memang menunjukkan ketahanan dan motivasi tinggi dalam menempuh pendidikan, tetapi ini juga seringkali didorong oleh faktor struktural—seperti minimnya akses pekerjaan formal bagi perempuan—terlepas dari keinginan diri sendiri— memaksa mereka memperpanjang masa studi. Keterangan data yang ditunjukan oleh BPS Provinsi Gorontalo terkait dengan ketidakmerataan pendidikan (khususnya laki-laki), itu akibat dari tak ada biaya dan jarak ke sekolah yang jauh.
Namun, yang perlu untuk kita bedah, adalah bagaimana alokasi anggaran pemerintah daerah. Jikapun, keterbelakangan ini akibat dari kurangnya materi dan biaya, harusnya pemerintah daerah kembali mengevaluasi terkait pemberian bantuan, salah satunya Beasiswa atau semacamnya.
Berdasarkan laporan APBD Provinsi Gorontalo tahun 2023, tercatat bahwa belanja bantuan sosial mencapai angka fantastis: Rp. 25.573.289.935,00 atau kurang lebih 86,75 persen dari total belanja bantuan sosial.
Besarnya anggaran ini seharusnya mampu mengurangi disparitas akses ke pendidikan. Tidak cukup hanya dengan membangun gedung sekolah, tetapi juga perlu memastikan bahwa penerima bantuan pendidikan tepat sasaran—beasiswa dan subsidi harus menjangkau siswa atau calon siswa di daerah tertinggal dan keluarga prasejahtera.
Lebih dari sekadar angka statistik, pendidikan adalah hak asasi manusia yang tak boleh dikompromikan. Apabila kita gagal mewujudkan pemerataan pendidikan, maka kita sedang mewariskan ketimpangan antargenerasi yang lebih dalam. Jika itu terjadi, harusnya ini lebih menakutkan dari berita tsunami.
PENDIDIKAN TIDAK MERATA, PEKERJAAN YANG SULIT TERCIPTA
Masalah lapangan pekerjaan di Provinsi Gorontalo bukan hanya soal ketersediaan peluang, tetapi juga soal kualitas dan kesiapan tenaga kerja. Dalam konteks ini, “Ketidakmerataan Pendidikan” memiliki korelasi langsung dan signifikan terhadap terbatasnya peluang kerja yang layak.
Di daerah-daerah yang tingkat pendidikannya timpang, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir, sumber daya manusia cenderung tidak memiliki keterampilan dan kapasitas yang dibutuhkan oleh sektor industri modern. Akibatnya, sebagian besar angkatan kerja hanya dapat mengakses pekerjaan di sektor informal, pertanian tradisional, atau pekerjaan kasual dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial.
Ini menciptakan jebakan struktural: masyarakat tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan karena pekerjaan yang tersedia bersifat subsisten, sementara sektor ekonomi tidak bisa tumbuh karena kekurangan tenaga kerja terampil. Ketika tenaga kerja tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, maka investasi pun enggan masuk. Dunia usaha mencari wilayah dengan ekosistem SDM yang siap pakai—dan Gorontalo belum menawarkan itu secara merata.
Ketimpangan pendidikan ini juga memperbesar kesenjangan antarwilayah dalam hal kesempatan kerja. Wilayah yang memiliki akses lebih baik ke pendidikan akan melahirkan tenaga kerja yang lebih siap bersaing, sementara wilayah lain terus tertinggal. Ini membuat mobilitas sosial menjadi stagnan, dan menjadikan pasar kerja Gorontalo sangat sempit bagi mereka yang tidak memiliki ijazah atau keterampilan khusus.
Tak hanya itu, pemerintah daerah sering gagal membaca korelasi ini secara menyeluruh. Kebijakan penciptaan lapangan kerja yang tidak dibarengi dengan strategi peningkatan kualitas tenaga kerja hanya akan menghasilkan pekerjaan jangka pendek, tidak berkelanjutan, dan berisiko tinggi mengalami stagnasi. Bahkan program-program pemberdayaan yang digelontorkan hanya menjadi formalitas jika tidak melibatkan pelatihan berbasis kebutuhan nyata pasar tenaga kerja.
Dalam jangka panjang, ketidakmerataan pendidikan akan terus menjadi hambatan bagi pertumbuhan lapangan kerja berkualitas di Gorontalo. Dengan kata lain, lapangan pekerjaan tidak akan berkembang dalam ruang hampa. Ia tumbuh di atas fondasi kualitas SDM yang merata. Dan selama pendidikan—sebagai pintu awal peningkatan kualitas SDM—masih timpang, maka Gorontalo akan terus bergulat dengan masalah pengangguran terselubung, pekerjaan informal, dan ekonomi yang tidak berdaya saing.
KETIKA LAPANGAN PEKERJAAN TAK ADA: DIBUNUH SECARA STRUKTUR.
Dalam laporan-laporan resmi, kita sering disodori angka-angka statistik yang seolah menggambarkan kondisi yang “masih terkendali. Lebih dari sekadar data, ini adalah tanda kematian struktural terhadap harapan generasi muda. Mereka tumbuh dalam sistem yang menjanjikan pekerjaan setelah sekolah, tetapi ketika mereka lulus, tak ada ruang untuk bekerja secara layak. Tak ada industri besar, tak ada inovasi ekonomi, dan tak ada ruang tumbuh bagi mereka yang ingin mandiri.
Keresahan ini bukan semata soal ekonomi, melainkan soal politik struktural yang secara sadar atau tidak telah “membunuh” cita-cita masyarakat. Pemerintah, yang seharusnya hadir sebagai pengarah dan penjamin pembangunan, justru menjadi bagian dari sistem yang mempermainkan masa depan rakyatnya. Anggaran dikucurkan, program diluncurkan, tetapi hasilnya tidak pernah menyentuh jantung persoalan: penciptaan pekerjaan yang riil dan berkelanjutan.
Yang terjadi justru sebaliknya: pekerjaan-pekerjaan muncul dalam bentuk proyek temporer, tenaga honor, atau pekerjaan yang hanya muncul menjelang pemilu. Semua dikemas sebagai pencapaian, padahal sesungguhnya hanya kamuflase dari sistem yang lumpuh. Lapangan kerja dikendalikan oleh kekuasaan, dan siapa yang tidak masuk dalam jaringan itu (tidak punya orang dalam), maka tak akan kebagian kesempatan itu.
Inilah wajah sistem yang tak hanya abai, tapi juga menindas. Ketiadaan lapangan kerja bukan karena masyarakat tidak mau bekerja, tapi karena ruangnya memang tidak pernah dibuka. Di tengah kondisi ini, muncul lapisan pengangguran terdidik yang frustrasi, kehilangan arah, dan merasa tak lagi punya tempat di tanah kelahirannya sendiri.
Lalu siapa yang salah? Tentu bukan rakyat, bukan pula anak-anak muda yang mencoba bertahan hidup di tengah kelangkaan. Yang salah adalah sistem yang membungkam, menutup akses, dan mempermainkan hak dasar manusia untuk bekerja. Negara tidak hanya gagal menciptakan lapangan kerja, tapi juga gagal menciptakan harapan.
KESIMPULAN
Ketakutan atas ancaman tsunami hanyalah satu dari sekian banyak kegelisahan yang kini menyelimuti masyarakat Gorontalo. Tapi lebih dari sekadar bencana alam, ketakutan yang paling nyata justru datang dari sistem sosial yang tak memberi kepastian: pendidikan yang tak merata, lapangan pekerjaan yang tak tersedia, dan pemerintahan yang tak mampu menjamin masa depan warganya.
Tsunami mungkin datang sesekali, namun tsunami ketimpangan sosial terjadi setiap hari, menggerus harapan secara perlahan. Di satu sisi, anak-anak muda Gorontalo sulit menjangkau pendidikan tinggi yang berkualitas. Di sisi lain, mereka yang telah menamatkan pendidikan justru mendapati bahwa tak ada ruang kerja yang menunggu. Mereka seolah disuruh belajar untuk sesuatu yang tidak pernah disiapkan oleh negara: masa depan.
Kekosongan lapangan kerja, ketimpangan akses pendidikan, dan kecemasan hidup yang tak pasti—semuanya berakar pada kegagalan sistemik. Pemerintah tidak hanya lalai dalam tugasnya, tapi juga secara struktural membiarkan rakyat dibungkam oleh keadaan, alih-alih membebaskan mereka dari keterbelakangan.
Karena itu, yang dibutuhkan Gorontalo bukan hanya sirine peringatan bencana, tetapi perubahan mendalam pada cara berpikir dan merancang masa depan. Agar rakyat tidak terus hidup dalam ketakutan yang dipelihara oleh alam dan disempurnakan oleh negara.
- Adnan R. Abas; penulis sementara menyelesaikan studi S1-nya di Jurusan Akuntansi UNG; juga aktif dalam gerakan literasi, dan tempat ia bersemayam (belajar) paling banyak yakni di HMI Cabang Gorontalo.