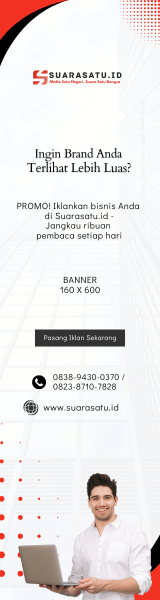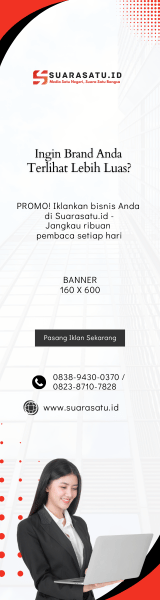Setelah mengamati dengan saksama lapisan-lapisan kekisruhan yang menyerang Dheninda “Dini” Chaerunnisa, ada sebuah pola yang jauh lebih busuk daripada sekadar pengalihan isu calo P3K. Ini bukan lagi perdebatan kebijakan yang sehat. Ini adalah pameran telanjang dari politik patriarki primitif.
Serangan terhadap Dini terlihat begitu brutal dan terkoordinasi bukan semata-mata karena substansi calo yang ia suarakan—meskipun itu adalah pemicu utamanya. Bahan bakar yang membuat api ini begitu besar adalah fakta sederhana bahwa dia adalah perempuan.
Seorang perempuan muda, vokal, dan kritis, dalam panggung politik yang masih didominasi mentalitas feodal, adalah sebuah “gangguan”. Perempuan, dalam kacamata kolot mereka, “seharusnya” diam, “seharusnya” santun, dan “seharusnya” tidak membuat gaduh dengan membongkar borok.
Ketika Dini tidak memenuhi ekspektasi lama itu, para penjaga sistem ini panik.
Dan apa yang mereka serang? Tentu saja bukan gagasannya. Mereka tidak akan pernah sanggup berdebat secara terbuka melawan data dan fakta soal praktik percaloan. Mereka menyerang satu-satunya hal yang paling mudah diserang dari seorang perempuan: dirinya, tubuhnya, dan ekspresinya.
Mereka mempolitisasi senyumnya. Mereka mengadili gesturnya. Ini adalah manual misoginis paling klasik di dunia.
Perhatikan permainannya: Jika seorang politisi laki-laki senior tersenyum sinis, itu akan disebut “strategi” atau “cerdik”. Tapi ketika Dini tersenyum—yang dalam konteksnya adalah upaya menahan diri di tengah riuh—itu diviralkan sebagai “kesombongan”. Laki-laki yang vokal adalah “tegas” dan “berani”; perempuan yang vokal adalah “emosional” dan “tidak beretika”.
Ini adalah body policing yang terang-terangan. Sebuah upaya rendah untuk menghakimi fisik karena mereka tidak mampu menghakimi otak.
Tujuannya sangat jelas: menghancurkan kredibilitas personalnya. Mereka ingin menciptakan narasi “Jangan percaya Dini, dia orangnya sombong,” dengan harapan publik akan lupa pada substansi pesannya. Ini adalah upaya delegitimasi karakter agar isu calo yang genting itu ikut mati terkubur.
Dan pola ini selalu sama. Ketika serangan terhadap ekspresi dianggap belum cukup, mereka akan mulai menyeret ranah privat. Keluarga akan dibawa-bawa, masa lalu orang tua akan diungkit, dan kehidupan pribadinya akan dijadikan bahan gosip.
Ini bukan lagi kritik. Ini adalah teror personal yang dirancang untuk menghancurkan mental, menciptakan trauma, dan memaksa suara kritis itu diam selamanya.
Kita tidak bisa membiarkan praktik busuk ini menjadi normal. Jika kita diam hari ini, kita sedang merestui penggunaan teror berbasis gender dalam politik. Ini bukan lagi soal membela Dini sebagai seorang individu. Ini soal membela hak setiap perempuan Gorontalo untuk masuk ke ruang publik, berbicara dengan gagasannya, tanpa harus takut tubuhnya dihakimi atau keluarganya diteror.
Apa yang kita saksikan adalah ketakutan. Ketakutan para pengecut terhadap keberanian dan gagasan. Jika satu-satunya senjata yang mereka miliki adalah memelintir video, menyerang pribadi, dan menggosipkan keluarga—maka sesungguhnya, mereka sudah kalah telak.
Oleh: Hendrawan Dwikarunia Datukramat (Presiden BEM UNG 2023, Aktivis & Analis Gerakan Sosial)